- Teks
- Sejarah
Media and the paradoxes of pluralis
Media and the paradoxes of pluralism
Kari Karppinen
Theories and concepts, on which normative views of media and democracy build, have generally taken a pluralist or anti-essentialist turn in recent decades. While notions such as ‘media quality’ or ‘public interest’ are increasingly contested, pluralism and diversity not only have become indisputable values, but also rank among the few politically correct criteria for assessing media performance and regulation. Hardly anyone would disagree with the idea that citizens need to have access to a broad range of political views, cultural expressions and aesthetic experiences in the public sphere. The meaning and nature of pluralism as a normative principle, however, remain vague and arguably under-theorised.
Much of the confusion surrounding the notions of pluralism and diversity in media studies undoubtedly stems from their disparate uses in different contexts, but there is also a certain ambiguity inherent in the concept of pluralism itself. As Gregor McLennan (1995: 7) has noted, the constitutive vagueness of pluralism as a social value gives it enough ideological flexibility for it to be capable of signifying reactionary tendencies in one phase of the debate and progressive values in the next. Pluralism thus constitutes a highly contentious and elusive principle in political and social theory as well as for evaluating the performance of the media.
Taking some distance from the attractiveness of commonsense pluralism, this chapter focuses on some paradoxical dimensions in the present discussion on pluralism and the public sphere. Reflecting the renewed emphasis on pluralism in political theory, normative models of deliberative democracy and the public sphere have been increasingly criticised for overemphasising social unity and rational consensus. Instead of a singular notion of the public sphere, public use of reason or the common good, theorists increasingly stress the plurality of public spheres, politics of difference and the complexity of ways in which the media can contribute to democracy. As a result, various radical-pluralist theories of democracy that have attempted to develop less rigidly normative conceptions of democracy and the public sphere have gained more and more prominence also in media studies. In contrast to the allegedly rationalistic and monistic thrust of the Habermasian public sphere approach, they are often seen to resonate better with the chaotic and complex nature of the contemporary media landscape.
I discuss the implications and potential significance of the radicalpluralist approach for media studies and media policy here by drawing mainly from the political philosophy of Chantal Mouffe (1993, 2000, 2005), whose model of ‘agonistic pluralism’ constitutes one of the most prominent alternatives to deliberative conceptions of democracy. The rationale for this is twofold. First, agonistic pluralism provides a fundamental critique of the traditional Habermasian approach to the public sphere and democracy. Second, and perhaps more important, I argue that her ideas also provide an equally strong critique of ‘naive pluralism’ that celebrates all multiplicity and diversity without paying attention to the continued centrality of the questions of power and exclusion in the public sphere.
As McLennan (1995: 83–4) notes, one of the main problems with any ‘principled pluralist’ perspective remains how to conceptualise the need for pluralism and diversity without falling into the trap of flatness, relativism, indifference, and unquestioning acceptance of market-driven difference and consumer culture. While Mouffe’s approach itself is open to criticism on many fronts, it serves as a good starting point for illustrating some of the problems in debating the value of pluralism in media politics. The purpose of discussing the agonistic approach here is therefore not to argue for more pluralism as such. Instead, it serves to question the inclusiveness of current pluralistic discourses and emphasise the continued importance of analyzing relations of power in contemporary public spheres. While the problems of ‘naive pluralism’ are certainly not foreign to contemporary media policy, the agonistic model of democracy is discussed here as a possible theoretical basis for bringing the current ‘ethos of pluralisation’ to bear also on the level of media structures and politics.
The ambiguity of pluralism
The idea of pluralism as a crucial social and political value is nothing new. Premised on the impossibility of unambiguously establishing truth, right or good, especially in social and political affairs, pluralism is one of the constitutive tenets of liberal democracy. According to Mouffe (2000: 18), the acceptance of pluralism, understood as ‘the end of a substantive idea of the good life’, is the most important single defining feature of modern liberal democracy that differentiates it from ancient models of democracy.
At its broadest definition, pluralism can simply be defined as a theorized preference for multiplicity over unity and diversity over uniformity in whatever field of enquiry (McLennan 1995: 25). In this sense, almost all particular discourses could be conceived as reflecting some aspect of the pluralism/monism interface, and for McLennan, rather than as a specific ideology, pluralism is best conceived as a general intellectual orientation, whose specific manifestations would be expected to change depending on the context.
Despite, or perhaps because of, its ubiquitous nature, it can be argued that sometimes pluralism itself has become the new foundation of social theory. John Keane (1992), for instance, has argued that political values of democracy and freedom of speech themselves should be conceived as means and necessary preconditions of protecting philosophical and political pluralism, rather than as foundational principles themselves. While accepting multiplicity and pluralism has become almost endemic to recent social theory, various universal forms of politics have given way to a new pluralist imaginary associated with identity politics and politics of difference (see Benhabib 2002). As Anne Phillips (2000: 238) notes, there has been ‘an explosion of new literature on what are seen as the challenges of diversity and difference’ – which according to Bonnie Honig (1996: 60) is ‘just another word for what used to be called pluralism’.
Instead of the utopia of a rationally based unitary public sphere, many argue that democracy needs to be seen as pluralised and marked by new kinds of politics of difference. For writers like Keane the ideal of a unified public sphere and its corresponding vision of a unitary public of citizens are becoming increasingly obsolete. Similarly, in media studies, Elizabeth Jacka (2003: 183) has argued that, instead of universal visions of the common good, democracy needs to be seen as based on ‘pragmatic and negotiated exchanges about ethical behaviour and ethically inspired courses of action’, and we need to ‘countenance a plurality of communication media and modes in which such a diverse set of exchanges will occur’. Such a pluralist approach would then be inclusive of different genres of media texts and different forms of media organisation, not privileging ‘high modern journalism’ as a superior form of rational communication.
In the context of the media, the attraction of pluralism would seem to be closely linked to the attacks on universal quality criteria or other unambiguous criteria for assessing media performance. In this sense, pluralism not only constitutes a perspective for assessing the performance of the media but also a form of political rationality that directly concerns media policy. According to Nielsen (2003), the ideas that all forms of culture contain their own criteria of quality have broken the universal basis for defining cultural quality and have led to a ‘pluralistic consensus’ in media and cultural policy. The notions of quality, cultural value or public interest are thus increasingly conceived in a relativist manner, avoiding the paternalism of the old paradigm of media policy.
The problem with the pluralistic consensus, however, lies in the ambiguity of pluralism as a normative principle. In a general sense, we are all pluralists, but on closer analysis it seems that the emphasis on pluralism and diversity will inevitably create its own pathologies and paradoxes. Pluralism and diversity may remain inherently good, but, as McLennan (1995: 8) writes, in deconstructing their value we are faced with questions of the following order. Is there not a point at which healthy diversity turns into unhealthy dissonance? Does pluralism mean that anything goes? And what exactly are the criteria for stopping the potentially endless multiplication of valid ideas?
According to Louise Marcil-Lacoste (1992), pluralism entails a certain ambiguity ‘between the over-full and the empty’: on the one hand, pluralism suggests abundance, flowering and expansion of values and choices, but, on the other hand, it also evokes emptiness. To recognize or promote plurality in some context is to say nothing about the nature of its elements and issues, their relations, and value. Stemming from this, pluralism can combine both critique and evasion. It involves critique of all monisms and it aims to deconstruct their foundational claims. Yet there is also evasion, in terms of its refusal to develop substantive normative positions concerning social, political and economic processes (ibid.).
Kari Karppinen
Theories and concepts, on which normative views of media and democracy build, have generally taken a pluralist or anti-essentialist turn in recent decades. While notions such as ‘media quality’ or ‘public interest’ are increasingly contested, pluralism and diversity not only have become indisputable values, but also rank among the few politically correct criteria for assessing media performance and regulation. Hardly anyone would disagree with the idea that citizens need to have access to a broad range of political views, cultural expressions and aesthetic experiences in the public sphere. The meaning and nature of pluralism as a normative principle, however, remain vague and arguably under-theorised.
Much of the confusion surrounding the notions of pluralism and diversity in media studies undoubtedly stems from their disparate uses in different contexts, but there is also a certain ambiguity inherent in the concept of pluralism itself. As Gregor McLennan (1995: 7) has noted, the constitutive vagueness of pluralism as a social value gives it enough ideological flexibility for it to be capable of signifying reactionary tendencies in one phase of the debate and progressive values in the next. Pluralism thus constitutes a highly contentious and elusive principle in political and social theory as well as for evaluating the performance of the media.
Taking some distance from the attractiveness of commonsense pluralism, this chapter focuses on some paradoxical dimensions in the present discussion on pluralism and the public sphere. Reflecting the renewed emphasis on pluralism in political theory, normative models of deliberative democracy and the public sphere have been increasingly criticised for overemphasising social unity and rational consensus. Instead of a singular notion of the public sphere, public use of reason or the common good, theorists increasingly stress the plurality of public spheres, politics of difference and the complexity of ways in which the media can contribute to democracy. As a result, various radical-pluralist theories of democracy that have attempted to develop less rigidly normative conceptions of democracy and the public sphere have gained more and more prominence also in media studies. In contrast to the allegedly rationalistic and monistic thrust of the Habermasian public sphere approach, they are often seen to resonate better with the chaotic and complex nature of the contemporary media landscape.
I discuss the implications and potential significance of the radicalpluralist approach for media studies and media policy here by drawing mainly from the political philosophy of Chantal Mouffe (1993, 2000, 2005), whose model of ‘agonistic pluralism’ constitutes one of the most prominent alternatives to deliberative conceptions of democracy. The rationale for this is twofold. First, agonistic pluralism provides a fundamental critique of the traditional Habermasian approach to the public sphere and democracy. Second, and perhaps more important, I argue that her ideas also provide an equally strong critique of ‘naive pluralism’ that celebrates all multiplicity and diversity without paying attention to the continued centrality of the questions of power and exclusion in the public sphere.
As McLennan (1995: 83–4) notes, one of the main problems with any ‘principled pluralist’ perspective remains how to conceptualise the need for pluralism and diversity without falling into the trap of flatness, relativism, indifference, and unquestioning acceptance of market-driven difference and consumer culture. While Mouffe’s approach itself is open to criticism on many fronts, it serves as a good starting point for illustrating some of the problems in debating the value of pluralism in media politics. The purpose of discussing the agonistic approach here is therefore not to argue for more pluralism as such. Instead, it serves to question the inclusiveness of current pluralistic discourses and emphasise the continued importance of analyzing relations of power in contemporary public spheres. While the problems of ‘naive pluralism’ are certainly not foreign to contemporary media policy, the agonistic model of democracy is discussed here as a possible theoretical basis for bringing the current ‘ethos of pluralisation’ to bear also on the level of media structures and politics.
The ambiguity of pluralism
The idea of pluralism as a crucial social and political value is nothing new. Premised on the impossibility of unambiguously establishing truth, right or good, especially in social and political affairs, pluralism is one of the constitutive tenets of liberal democracy. According to Mouffe (2000: 18), the acceptance of pluralism, understood as ‘the end of a substantive idea of the good life’, is the most important single defining feature of modern liberal democracy that differentiates it from ancient models of democracy.
At its broadest definition, pluralism can simply be defined as a theorized preference for multiplicity over unity and diversity over uniformity in whatever field of enquiry (McLennan 1995: 25). In this sense, almost all particular discourses could be conceived as reflecting some aspect of the pluralism/monism interface, and for McLennan, rather than as a specific ideology, pluralism is best conceived as a general intellectual orientation, whose specific manifestations would be expected to change depending on the context.
Despite, or perhaps because of, its ubiquitous nature, it can be argued that sometimes pluralism itself has become the new foundation of social theory. John Keane (1992), for instance, has argued that political values of democracy and freedom of speech themselves should be conceived as means and necessary preconditions of protecting philosophical and political pluralism, rather than as foundational principles themselves. While accepting multiplicity and pluralism has become almost endemic to recent social theory, various universal forms of politics have given way to a new pluralist imaginary associated with identity politics and politics of difference (see Benhabib 2002). As Anne Phillips (2000: 238) notes, there has been ‘an explosion of new literature on what are seen as the challenges of diversity and difference’ – which according to Bonnie Honig (1996: 60) is ‘just another word for what used to be called pluralism’.
Instead of the utopia of a rationally based unitary public sphere, many argue that democracy needs to be seen as pluralised and marked by new kinds of politics of difference. For writers like Keane the ideal of a unified public sphere and its corresponding vision of a unitary public of citizens are becoming increasingly obsolete. Similarly, in media studies, Elizabeth Jacka (2003: 183) has argued that, instead of universal visions of the common good, democracy needs to be seen as based on ‘pragmatic and negotiated exchanges about ethical behaviour and ethically inspired courses of action’, and we need to ‘countenance a plurality of communication media and modes in which such a diverse set of exchanges will occur’. Such a pluralist approach would then be inclusive of different genres of media texts and different forms of media organisation, not privileging ‘high modern journalism’ as a superior form of rational communication.
In the context of the media, the attraction of pluralism would seem to be closely linked to the attacks on universal quality criteria or other unambiguous criteria for assessing media performance. In this sense, pluralism not only constitutes a perspective for assessing the performance of the media but also a form of political rationality that directly concerns media policy. According to Nielsen (2003), the ideas that all forms of culture contain their own criteria of quality have broken the universal basis for defining cultural quality and have led to a ‘pluralistic consensus’ in media and cultural policy. The notions of quality, cultural value or public interest are thus increasingly conceived in a relativist manner, avoiding the paternalism of the old paradigm of media policy.
The problem with the pluralistic consensus, however, lies in the ambiguity of pluralism as a normative principle. In a general sense, we are all pluralists, but on closer analysis it seems that the emphasis on pluralism and diversity will inevitably create its own pathologies and paradoxes. Pluralism and diversity may remain inherently good, but, as McLennan (1995: 8) writes, in deconstructing their value we are faced with questions of the following order. Is there not a point at which healthy diversity turns into unhealthy dissonance? Does pluralism mean that anything goes? And what exactly are the criteria for stopping the potentially endless multiplication of valid ideas?
According to Louise Marcil-Lacoste (1992), pluralism entails a certain ambiguity ‘between the over-full and the empty’: on the one hand, pluralism suggests abundance, flowering and expansion of values and choices, but, on the other hand, it also evokes emptiness. To recognize or promote plurality in some context is to say nothing about the nature of its elements and issues, their relations, and value. Stemming from this, pluralism can combine both critique and evasion. It involves critique of all monisms and it aims to deconstruct their foundational claims. Yet there is also evasion, in terms of its refusal to develop substantive normative positions concerning social, political and economic processes (ibid.).
0/5000
Media dan paradoks pluralismeKari KarppinenTeori dan konsep-konsep, yang normatif pandangan membangun media dan demokrasi, umumnya telah mengambil majemuk atau anti-essentialist berubah dalam beberapa dekade terakhir. Sedangkan pengertian seperti 'media kualitas' atau 'kepentingan publik' semakin digugat, pluralisme dan keragaman tidak hanya telah menjadi nilai-nilai yang tak terbantahkan, tetapi juga peringkat di antara beberapa kriteria benar secara politis untuk menilai kinerja media dan peraturan. Hampir tidak ada orang akan setuju dengan ide bahwa warga negara harus memiliki akses ke berbagai pandangan politik, ekspresi budaya dan estetika pengalaman di ruang publik. Makna dan sifat pluralisme sebagai prinsip normatif, namun, tetap tidak jelas dan dapat dikatakan di bawah berteori.Banyak kebingungan seputar pengertian tentang pluralisme dan keragaman dalam studi media pasti berasal dari menggunakan mereka berbeda dalam konteks yang berbeda, tapi ada juga ambiguitas tertentu yang melekat dalam konsep pluralisme itu sendiri. Seperti Gregor McLennan (1995:7) telah dicatat, ketidakjelasan konstitutif pluralisme sebagai nilai sosial memberikan fleksibilitas cukup ideologi untuk itu harus mampu menandakan kecenderungan reaksioner dalam fase satu perdebatan dan nilai-nilai yang progresif di berikutnya. Pluralisme sehingga merupakan sebuah prinsip yang sangat diperdebatkan dan sukar dipahami dalam politik dan sosial teori serta untuk mengevaluasi kinerja media.Mengambil beberapa jarak dari daya tarik pluralisme akal sehat, Bab ini berfokus pada beberapa dimensi paradoks dalam diskusi hadir pada pluralisme dan ruang publik. Mencerminkan penekanan baru pada pluralisme di bidang teori politik, normatif model deliberatif demokrasi dan ruang publik telah semakin dikritik untuk overemphasising kesatuan sosial dan rasional konsensus. Daripada pengertian tunggal ruang publik, umum penggunaan alasan atau kebaikan bersama, teori semakin menekankan pluralitas bola umum, politik perbedaan dan kompleksitas dari cara di mana media dapat berkontribusi untuk demokrasi. Sebagai hasilnya, berbagai teori radikal-majemuk demokrasi yang telah berusaha untuk mengembangkan konsepsi kurang kaku normatif demokrasi dan ruang publik telah memperoleh lebih banyak dan lebih menonjol juga dalam studi media. Berbeda dengan dorong diduga berfalsafah dan monistic pendekatan ruang publik Habermasian, mereka sering terlihat untuk beresonansi lebih baik dengan kompleks dan kacau sifat dari lanskap media kontemporer.Saya membahas implikasi dan potensi makna dari pendekatan radicalpluralist untuk studi media dan kebijakan media di sini dengan menggambar terutama dari Filsafat politik Chantal Mouffe (1993, 2000, 2005), yang model 'agonistic pluralisme' yang merupakan salah satu alternatif yang paling menonjol untuk deliberatif konsepsi demokrasi. Alasan untuk ini ada dua. Pertama, agonistic pluralisme menyediakan kritik mendasar dari pendekatan Habermasian tradisional ruang publik dan demokrasi. Kedua, dan mungkin lebih penting, saya berpendapat bahwa ide-ide nya juga memberikan sebuah kritik yang sama kuat 'naif pluralisme' yang merayakan semua keserbaragaman dan keragaman tanpa memperhatikan pentingnya terus pertanyaan kekuasaan dan pengecualian di ruang publik.Sebagai McLennan (1995: 83-4) catatan, salah satu masalah utama dengan perspektif 'berprinsip majemuk' tetap bagaimana untuk conceptualise kebutuhan pluralisme dan keragaman tanpa jatuh ke dalam perangkap kerataan, relativisme, ketidakpedulian, dan tidak perlu diragukan lagi penerimaan didorong pasar konsumen dan perbedaan budaya. Sementara Mouffe's pendekatan itu sendiri terbuka terhadap kritik di banyak bidang, ini berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk menggambarkan beberapa masalah yang memperdebatkan nilai pluralisme dalam politik media. Tujuan membahas agonistic pendekatan di sini adalah tidak untuk berdebat untuk lebih pluralisme seperti itu. Sebaliknya, ini berfungsi untuk pertanyaan inklusif dari wacana pluralistik saat ini dan menekankan pentingnya terus menganalisa hubungan kekuasaan di bidang umum kontemporer. Sementara masalah 'naif pluralisme' tentu tidak asing bagi kebijakan media kontemporer, model agonistic demokrasi yang dibahas di sini sebagai secara teoritis mungkin untuk membawa arus 'etos pluralisation' untuk menanggung juga pada tingkat struktur media dan politik.Ambiguitas pluralismeGagasan pluralisme sebagai nilai sosial dan politik yang penting bukanlah hal baru. Berdasarkan kemustahilan pembentukan jelas kebenaran, benar atau baik, terutama dalam urusan sosial dan politik, pluralisme adalah salah satu ajaran konstitutif dari demokrasi liberal. Menurut Mouffe (2000:18), penerimaan pluralisme, dipahami sebagai 'akhir ide yang substantif dari kehidupan yang baik', adalah fitur mendefinisikan tunggal paling penting demokrasi liberal modern yang membedakan dari kuno model demokrasi.Definisi yang luas, pluralisme dapat hanya didefinisikan sebagai preferensi theorized untuk keserbaragaman atas kesatuan dan keragaman atas keseragaman dalam bidang apa pun pertanyaan (McLennan 1995:25). Dalam pengertian ini, hampir semua wacana tertentu bisa dipahami sebagai mencerminkan beberapa aspek dari antarmuka pluralisme monisme, dan untuk McLennan, daripada sebagai ideologi tertentu, pluralisme terbaik dipahami sebagai orientasi intelektual yang umum, manifestasi tertentu yang akan diharapkan untuk mengubah tergantung pada konteks.Meskipun, atau mungkin karena, mana-mana alam, dapat dikatakan bahwa kadang-kadang pluralisme itu sendiri telah menjadi dasar teori sosial baru. John Keane (1992), sebagai contoh, telah berpendapat bahwa politik nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berbicara sendiri harus dipahami sebagai sarana dan prasyarat yang diperlukan untuk melindungi pluralisme filsafat dan politik, bukan sebagai prinsip-prinsip dasar sendiri. Sementara menerima keserbaragaman dan pluralisme telah menjadi hampir endemik hari teori sosial, berbagai bentuk universal politik telah memberikan cara untuk imajiner majemuk baru yang terkait dengan politik identitas dan politik perbedaan (Lihat Benhabib 2002). Sebagai catatan Anne Phillips (2000:238), telah ada 'ledakan baru literatur tentang apa yang dilihat sebagai tantangan keragaman dan perbedaan'-yang menurut Bonnie Honig (1996:60) adalah 'kata lain untuk apa yang dulu disebut pluralisme'.Bukan utopia rasional berdasarkan ruang publik kesatuan, banyak yang berpendapat bahwa demokrasi perlu dilihat sebagai pluralised dan ditandai oleh jenis baru mengenai politik dalam perbedaan. Untuk penulis seperti Keane ideal ruang publik bersatu dan sesuai visi umum kesatuan warga menjadi semakin usang. Demikian pula, dalam studi media, Elizabeth Jacka (2003:183) berpendapat bahwa, bukan visi universal kesejahteraan umum, demokrasi perlu dilihat sebagai berdasarkan 'pragmatis dan negosiasi pertukaran tentang perilaku etika dan etis terinspirasi kursus tindakan', dan kita perlu 'wajah pluralitas media komunikasi dan mode sedemikian yang beragam set pertukaran akan terjadi'. Sebuah pendekatan majemuk akan termasuk genre yang berbeda media teks dan berbagai bentuk organisasi media, tidak privileging 'tinggi modern jurnalisme' sebagai bentuk unggul rasional komunikasi.Dalam konteks media, daya tarik pluralisme tampaknya menjadi erat terkait dengan serangan terhadap kriteria kualitas universal atau kriteria lainnya tidak ambigu menilai kinerja media. Dalam pengertian ini, pluralisme tidak hanya merupakan sebuah perspektif untuk menilai kinerja media tapi juga bentuk rasionalitas politik yang secara langsung mengenai kebijakan media. Menurut Nielsen (2003), ide-ide bahwa semua bentuk budaya berisi kriteria mereka sendiri kualitas telah melanggar dasar universal mendefinisikan budaya kualitas dan telah menyebabkan 'konsensus pluralistik' di media dan budaya kebijakan. Pengertian tentang kualitas, nilai budaya atau kepentingan publik sehingga semakin dipahami secara relativist, menghindari Paternalisme paradigma lama kebijakan media.Masalah dengan konsensus pluralistik, namun, terletak di ambiguitas pluralisme sebagai prinsip normatif. Dalam pengertian umum, kita semua pluralists, tapi pada analisa yang lebih tampaknya bahwa penekanan pada keberagaman dan kemajemukan pasti akan membuat sendiri patologi dan paradoks. Pluralisme dan keragaman dapat tetap baik, tetapi, sebagai menulis McLennan (1995:8), dalam membongkar nilai mereka kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari urutan sebagai berikut. Apakah tidak ada titik di mana sehat keragaman berubah menjadi disonansi tidak sehat? Apakah pluralisme berarti bahwa apa pun yang terjadi? Dan apa sebenarnya yang kriteria untuk menghentikan perkalian berpotensi tak berujung dari ide-ide yang berlaku?Menurut Louise Marcil-Lacoste (1992), pluralisme memerlukan ambiguitas tertentu 'antara penuh over dan kosong': di satu sisi, pluralisme menunjukkan kelimpahan, berbunga dan perluasan nilai-nilai dan pilihan, tetapi, di sisi lain, ini juga membangkitkan kekosongan. Untuk mengenali atau mempromosikan pluralitas pribadi dalam beberapa konteks adalah untuk mengatakan apa-apa tentang sifat dari unsur-unsur dan isu-isu, hubungan, dan nilai. Berasal dari ini, pluralisme dapat menggabungkan kedua kritik dan penghindaran. Ini melibatkan kritik dari semua monisms dan bertujuan untuk mendekonstruksi klaim dasar mereka. Namun ada juga penghindaran, dalam hal penolakan untuk mengembangkan substantif normatif posisi mengenai proses sosial, politik dan ekonomi (ibid.).
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
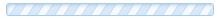
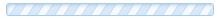
Media dan paradoks pluralisme
Kari Karppinen Teori dan konsep, yang dilihat normatif media dan demokrasi membangun, umumnya mengambil giliran pluralis atau anti-esensialis dalam beberapa dekade terakhir. Sementara pengertian seperti 'kualitas media yang' atau 'kepentingan umum' semakin diperebutkan, pluralisme dan keragaman tidak hanya telah menjadi nilai-nilai yang tak terbantahkan, tetapi juga peringkat di antara beberapa kriteria politik yang benar untuk menilai kinerja media dan regulasi. Hampir tidak ada orang yang tidak setuju dengan gagasan bahwa warga harus memiliki akses ke berbagai pandangan politik, ekspresi budaya dan pengalaman estetika dalam ruang publik. Arti dan sifat pluralisme sebagai prinsip normatif, bagaimanapun, tetap kabur dan bisa dibilang kurang berteori. Banyak kebingungan pengertian pluralisme dan keberagaman dalam studi media diragukan lagi berasal dari penggunaan yang berbeda dalam konteks yang berbeda, tetapi ada juga ambiguitas tertentu yang melekat dalam konsep pluralisme itu sendiri. Sebagai Gregor McLennan (1995: 7) telah mencatat, ketidakjelasan konstitutif pluralisme sebagai nilai sosial memberikan fleksibilitas yang cukup ideologis untuk itu harus mampu menandakan kecenderungan reaksioner dalam satu fase dari perdebatan dan nilai-nilai progresif dalam berikutnya. Pluralisme sehingga merupakan prinsip yang sangat kontroversial dan sulit dipahami dalam teori politik dan sosial serta untuk mengevaluasi kinerja media. Mengambil beberapa jarak dari daya tarik pluralisme akal sehat, bab ini berfokus pada beberapa dimensi paradoks dalam diskusi hadir pada pluralisme dan ranah publik. Mencerminkan penekanan baru tentang pluralisme dalam teori politik, model normatif demokrasi deliberatif dan ruang publik telah semakin dikritik karena overemphasising kesatuan sosial dan konsensus rasional. Alih-alih gagasan tunggal ruang publik, penggunaan publik alasan atau kepentingan umum, teori semakin menekankan pluralitas ruang publik, politik perbedaan dan kompleksitas cara di mana media dapat berkontribusi untuk demokrasi. Akibatnya, berbagai teori radikal-pluralis demokrasi yang telah berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep yang kurang kaku normatif demokrasi dan ruang publik telah mendapatkan lebih banyak dan lebih menonjol juga dalam studi media. Berbeda dengan dorong diduga rasionalistik dan monistik dari pendekatan ruang publik Habermasian, mereka sering terlihat untuk beresonansi baik dengan sifat kacau dan kompleks dari lanskap media kontemporer. Saya membahas implikasi dan signifikansi potensial dari pendekatan radicalpluralist untuk studi media dan kebijakan media di sini dengan menggambar terutama dari filsafat politik dari Chantal Mouffe (1993, 2000, 2005), Model yang dari 'pluralisme agonistik' merupakan salah satu alternatif yang paling menonjol untuk deliberatif konsepsi demokrasi. Alasan untuk ini adalah dua kali lipat. Pertama, pluralisme agonistik memberikan kritik mendasar dari pendekatan Habermasian tradisional untuk ruang publik dan demokrasi. Kedua, dan mungkin lebih penting, saya berpendapat bahwa ide-idenya juga memberikan kritik sama kuat dari 'pluralisme naif' yang merayakan semua keragaman dan keragaman tanpa memperhatikan sentralitas lanjutan dari pertanyaan kekuasaan dan eksklusi di ruang publik. Sebagai McLennan (1995: 83-4) catatan, salah satu masalah utama dengan 'berprinsip pluralis' perspektif tetap bagaimana untuk membuat konsep kebutuhan untuk pluralisme dan keragaman tanpa jatuh ke dalam perangkap kerataan, relativisme, ketidakpedulian, dan penerimaan tidak perlu diragukan lagi dari pasar-didorong Perbedaan dan budaya konsumen. Sementara pendekatan Mouffe sendiri terbuka untuk kritik di berbagai bidang, ia berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk menggambarkan beberapa masalah di memperdebatkan nilai pluralisme dalam politik media yang. Oleh karena itu tujuan membahas pendekatan atletik di sini bukan untuk berdebat untuk lebih pluralisme seperti itu. Sebaliknya, itu berfungsi untuk mempertanyakan inklusivitas wacana pluralis saat ini dan menekankan pentingnya terus menganalisis hubungan kekuasaan di ruang publik kontemporer. Sementara masalah 'pluralisme naif' tentu tidak asing dengan kebijakan media kontemporer, model agonistik demokrasi dibahas di sini sebagai dasar teoritis mungkin untuk membawa 'etos pluralisasi' saat menanggung juga pada tingkat struktur media dan politik . Ambiguitas pluralisme Ide pluralisme sebagai nilai sosial dan politik yang penting bukan hal yang baru. Didasarkan pada ketidakmungkinan jelas menetapkan kebenaran, benar atau baik, terutama dalam urusan sosial dan politik, pluralisme adalah salah satu prinsip konstitutif demokrasi liberal. Menurut Mouffe (2000: 18), penerimaan pluralisme, dipahami sebagai 'akhir ide substantif kehidupan yang baik', adalah yang paling penting ciri tunggal demokrasi liberal modern yang membedakan dengan model kuno demokrasi. Pada definisi luas yang, pluralisme sederhana dapat didefinisikan sebagai preferensi diteorikan untuk multiplisitas lebih kesatuan dan keberagaman lebih keseragaman dalam bidang apapun penyelidikan (McLennan 1995: 25). Dalam hal ini, hampir semua wacana tertentu dapat dipahami sebagai mencerminkan beberapa aspek dari antarmuka pluralisme / monisme, dan untuk McLennan, bukan sebagai ideologi tertentu, pluralisme terbaik dipahami sebagai orientasi intelektual umum, yang manifestasi tertentu akan diharapkan untuk berubah tergantung pada konteks. Meskipun, atau mungkin karena, sifat mana-mana, itu bisa dikatakan bahwa kadang-kadang pluralisme itu sendiri telah menjadi fondasi baru teori sosial. John Keane (1992), misalnya, berpendapat bahwa nilai-nilai politik demokrasi dan kebebasan berbicara sendiri harus dipahami sebagai sarana dan prasyarat yang diperlukan untuk melindungi filsafat dan politik pluralisme, bukan sebagai prinsip dasar sendiri. Saat menerima keragaman dan pluralisme telah menjadi hampir endemik teori sosial baru-baru ini, berbagai bentuk universal politik telah memberikan cara untuk pluralis imajiner baru yang terkait dengan politik identitas dan politik perbedaan (lihat Benhabib 2002). Seperti Anne Phillips (2000: 238) mencatat, telah terjadi 'ledakan sastra baru pada apa yang dilihat sebagai tantangan keragaman dan perbedaan' - yang menurut Bonnie Honig (1996: 60) adalah 'hanya kata lain untuk apa digunakan disebut pluralisme '. Alih-alih utopia dari ruang publik kesatuan berdasarkan rasional, banyak yang berpendapat bahwa demokrasi perlu dilihat sebagai pluralised dan ditandai dengan jenis baru dari politik perbedaan. Untuk penulis seperti Keane ideal dari ruang publik terpadu dan visi yang sesuai dari publik kesatuan warga menjadi semakin usang. Demikian pula, dalam studi media, Elizabeth Jacka (2003: 183) berpendapat bahwa, bukan visi universal kebaikan bersama, demokrasi perlu dilihat sebagai berdasarkan 'pertukaran pragmatis dan negosiasi tentang perilaku etis dan kursus terinspirasi etis tindakan', dan kita perlu 'menyetujui sejumlah media komunikasi dan mode di mana seperti beragam rangkaian pertukaran akan terjadi'. Pendekatan pluralis seperti itu akan termasuk genre yang berbeda dari teks-teks media dan berbagai bentuk organisasi media, tidak mengistimewakan 'tinggi jurnalisme modern sebagai bentuk superior komunikasi rasional. Dalam konteks media, tarik pluralisme tampaknya akan terkait erat dengan serangan terhadap kriteria kualitas yang universal atau kriteria ambigu lainnya untuk menilai kinerja media yang. Dalam pengertian ini, pluralisme tidak hanya merupakan perspektif untuk menilai kinerja media, tetapi juga bentuk rasionalitas politik yang secara langsung menyangkut kebijakan media. Menurut Nielsen (2003), ide bahwa semua bentuk budaya mengandung kriteria sendiri kualitas telah rusak dasar universal untuk mendefinisikan kualitas budaya dan telah menyebabkan 'konsensus pluralistik' di media dan kebijakan budaya. Pengertian tentang kualitas, nilai budaya atau kepentingan publik sehingga semakin dipahami secara relativis, menghindari paternalisme dari paradigma lama kebijakan media. Masalah dengan konsensus pluralistik, bagaimanapun, terletak pada ambiguitas pluralisme sebagai prinsip normatif. Dalam pengertian umum, kita semua pluralis, tetapi pada analisis lebih dekat tampaknya bahwa penekanan pada pluralisme dan keragaman pasti akan membuat patologi dan paradoks tersendiri. Pluralisme dan keragaman mungkin tetap inheren baik, tapi, seperti McLennan (1995: 8) menulis, di mendekonstruksi nilai mereka kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari urutan sebagai berikut. Apakah tidak ada titik di mana keanekaragaman sehat berubah menjadi disonansi tidak sehat? Apakah pluralisme berarti bahwa apa pun yang terjadi? Dan apa sebenarnya kriteria untuk menghentikan multiplikasi berpotensi tak berujung ide valid? Menurut Louise Marcil-Lacoste (1992), pluralisme memerlukan ambiguitas tertentu 'antara over-penuh dan kosong': di satu sisi, pluralisme menunjukkan kelimpahan , berbunga dan perluasan nilai dan pilihan, tetapi, di sisi lain, itu juga membangkitkan kekosongan. Untuk mengenali atau mempromosikan pluralitas dalam beberapa konteks adalah untuk mengatakan apa-apa tentang sifat unsur dan isu-isu, hubungan mereka, dan nilai. Berasal dari ini, pluralisme dapat menggabungkan kedua kritik dan penggelapan. Ini melibatkan kritik dari semua monisms dan bertujuan untuk mendekonstruksi klaim dasar mereka. Namun ada juga penggelapan, dalam hal penolakannya untuk mengembangkan posisi normatif substantif mengenai proses sosial, politik dan ekonomi (ibid.).
Kari Karppinen Teori dan konsep, yang dilihat normatif media dan demokrasi membangun, umumnya mengambil giliran pluralis atau anti-esensialis dalam beberapa dekade terakhir. Sementara pengertian seperti 'kualitas media yang' atau 'kepentingan umum' semakin diperebutkan, pluralisme dan keragaman tidak hanya telah menjadi nilai-nilai yang tak terbantahkan, tetapi juga peringkat di antara beberapa kriteria politik yang benar untuk menilai kinerja media dan regulasi. Hampir tidak ada orang yang tidak setuju dengan gagasan bahwa warga harus memiliki akses ke berbagai pandangan politik, ekspresi budaya dan pengalaman estetika dalam ruang publik. Arti dan sifat pluralisme sebagai prinsip normatif, bagaimanapun, tetap kabur dan bisa dibilang kurang berteori. Banyak kebingungan pengertian pluralisme dan keberagaman dalam studi media diragukan lagi berasal dari penggunaan yang berbeda dalam konteks yang berbeda, tetapi ada juga ambiguitas tertentu yang melekat dalam konsep pluralisme itu sendiri. Sebagai Gregor McLennan (1995: 7) telah mencatat, ketidakjelasan konstitutif pluralisme sebagai nilai sosial memberikan fleksibilitas yang cukup ideologis untuk itu harus mampu menandakan kecenderungan reaksioner dalam satu fase dari perdebatan dan nilai-nilai progresif dalam berikutnya. Pluralisme sehingga merupakan prinsip yang sangat kontroversial dan sulit dipahami dalam teori politik dan sosial serta untuk mengevaluasi kinerja media. Mengambil beberapa jarak dari daya tarik pluralisme akal sehat, bab ini berfokus pada beberapa dimensi paradoks dalam diskusi hadir pada pluralisme dan ranah publik. Mencerminkan penekanan baru tentang pluralisme dalam teori politik, model normatif demokrasi deliberatif dan ruang publik telah semakin dikritik karena overemphasising kesatuan sosial dan konsensus rasional. Alih-alih gagasan tunggal ruang publik, penggunaan publik alasan atau kepentingan umum, teori semakin menekankan pluralitas ruang publik, politik perbedaan dan kompleksitas cara di mana media dapat berkontribusi untuk demokrasi. Akibatnya, berbagai teori radikal-pluralis demokrasi yang telah berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep yang kurang kaku normatif demokrasi dan ruang publik telah mendapatkan lebih banyak dan lebih menonjol juga dalam studi media. Berbeda dengan dorong diduga rasionalistik dan monistik dari pendekatan ruang publik Habermasian, mereka sering terlihat untuk beresonansi baik dengan sifat kacau dan kompleks dari lanskap media kontemporer. Saya membahas implikasi dan signifikansi potensial dari pendekatan radicalpluralist untuk studi media dan kebijakan media di sini dengan menggambar terutama dari filsafat politik dari Chantal Mouffe (1993, 2000, 2005), Model yang dari 'pluralisme agonistik' merupakan salah satu alternatif yang paling menonjol untuk deliberatif konsepsi demokrasi. Alasan untuk ini adalah dua kali lipat. Pertama, pluralisme agonistik memberikan kritik mendasar dari pendekatan Habermasian tradisional untuk ruang publik dan demokrasi. Kedua, dan mungkin lebih penting, saya berpendapat bahwa ide-idenya juga memberikan kritik sama kuat dari 'pluralisme naif' yang merayakan semua keragaman dan keragaman tanpa memperhatikan sentralitas lanjutan dari pertanyaan kekuasaan dan eksklusi di ruang publik. Sebagai McLennan (1995: 83-4) catatan, salah satu masalah utama dengan 'berprinsip pluralis' perspektif tetap bagaimana untuk membuat konsep kebutuhan untuk pluralisme dan keragaman tanpa jatuh ke dalam perangkap kerataan, relativisme, ketidakpedulian, dan penerimaan tidak perlu diragukan lagi dari pasar-didorong Perbedaan dan budaya konsumen. Sementara pendekatan Mouffe sendiri terbuka untuk kritik di berbagai bidang, ia berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk menggambarkan beberapa masalah di memperdebatkan nilai pluralisme dalam politik media yang. Oleh karena itu tujuan membahas pendekatan atletik di sini bukan untuk berdebat untuk lebih pluralisme seperti itu. Sebaliknya, itu berfungsi untuk mempertanyakan inklusivitas wacana pluralis saat ini dan menekankan pentingnya terus menganalisis hubungan kekuasaan di ruang publik kontemporer. Sementara masalah 'pluralisme naif' tentu tidak asing dengan kebijakan media kontemporer, model agonistik demokrasi dibahas di sini sebagai dasar teoritis mungkin untuk membawa 'etos pluralisasi' saat menanggung juga pada tingkat struktur media dan politik . Ambiguitas pluralisme Ide pluralisme sebagai nilai sosial dan politik yang penting bukan hal yang baru. Didasarkan pada ketidakmungkinan jelas menetapkan kebenaran, benar atau baik, terutama dalam urusan sosial dan politik, pluralisme adalah salah satu prinsip konstitutif demokrasi liberal. Menurut Mouffe (2000: 18), penerimaan pluralisme, dipahami sebagai 'akhir ide substantif kehidupan yang baik', adalah yang paling penting ciri tunggal demokrasi liberal modern yang membedakan dengan model kuno demokrasi. Pada definisi luas yang, pluralisme sederhana dapat didefinisikan sebagai preferensi diteorikan untuk multiplisitas lebih kesatuan dan keberagaman lebih keseragaman dalam bidang apapun penyelidikan (McLennan 1995: 25). Dalam hal ini, hampir semua wacana tertentu dapat dipahami sebagai mencerminkan beberapa aspek dari antarmuka pluralisme / monisme, dan untuk McLennan, bukan sebagai ideologi tertentu, pluralisme terbaik dipahami sebagai orientasi intelektual umum, yang manifestasi tertentu akan diharapkan untuk berubah tergantung pada konteks. Meskipun, atau mungkin karena, sifat mana-mana, itu bisa dikatakan bahwa kadang-kadang pluralisme itu sendiri telah menjadi fondasi baru teori sosial. John Keane (1992), misalnya, berpendapat bahwa nilai-nilai politik demokrasi dan kebebasan berbicara sendiri harus dipahami sebagai sarana dan prasyarat yang diperlukan untuk melindungi filsafat dan politik pluralisme, bukan sebagai prinsip dasar sendiri. Saat menerima keragaman dan pluralisme telah menjadi hampir endemik teori sosial baru-baru ini, berbagai bentuk universal politik telah memberikan cara untuk pluralis imajiner baru yang terkait dengan politik identitas dan politik perbedaan (lihat Benhabib 2002). Seperti Anne Phillips (2000: 238) mencatat, telah terjadi 'ledakan sastra baru pada apa yang dilihat sebagai tantangan keragaman dan perbedaan' - yang menurut Bonnie Honig (1996: 60) adalah 'hanya kata lain untuk apa digunakan disebut pluralisme '. Alih-alih utopia dari ruang publik kesatuan berdasarkan rasional, banyak yang berpendapat bahwa demokrasi perlu dilihat sebagai pluralised dan ditandai dengan jenis baru dari politik perbedaan. Untuk penulis seperti Keane ideal dari ruang publik terpadu dan visi yang sesuai dari publik kesatuan warga menjadi semakin usang. Demikian pula, dalam studi media, Elizabeth Jacka (2003: 183) berpendapat bahwa, bukan visi universal kebaikan bersama, demokrasi perlu dilihat sebagai berdasarkan 'pertukaran pragmatis dan negosiasi tentang perilaku etis dan kursus terinspirasi etis tindakan', dan kita perlu 'menyetujui sejumlah media komunikasi dan mode di mana seperti beragam rangkaian pertukaran akan terjadi'. Pendekatan pluralis seperti itu akan termasuk genre yang berbeda dari teks-teks media dan berbagai bentuk organisasi media, tidak mengistimewakan 'tinggi jurnalisme modern sebagai bentuk superior komunikasi rasional. Dalam konteks media, tarik pluralisme tampaknya akan terkait erat dengan serangan terhadap kriteria kualitas yang universal atau kriteria ambigu lainnya untuk menilai kinerja media yang. Dalam pengertian ini, pluralisme tidak hanya merupakan perspektif untuk menilai kinerja media, tetapi juga bentuk rasionalitas politik yang secara langsung menyangkut kebijakan media. Menurut Nielsen (2003), ide bahwa semua bentuk budaya mengandung kriteria sendiri kualitas telah rusak dasar universal untuk mendefinisikan kualitas budaya dan telah menyebabkan 'konsensus pluralistik' di media dan kebijakan budaya. Pengertian tentang kualitas, nilai budaya atau kepentingan publik sehingga semakin dipahami secara relativis, menghindari paternalisme dari paradigma lama kebijakan media. Masalah dengan konsensus pluralistik, bagaimanapun, terletak pada ambiguitas pluralisme sebagai prinsip normatif. Dalam pengertian umum, kita semua pluralis, tetapi pada analisis lebih dekat tampaknya bahwa penekanan pada pluralisme dan keragaman pasti akan membuat patologi dan paradoks tersendiri. Pluralisme dan keragaman mungkin tetap inheren baik, tapi, seperti McLennan (1995: 8) menulis, di mendekonstruksi nilai mereka kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari urutan sebagai berikut. Apakah tidak ada titik di mana keanekaragaman sehat berubah menjadi disonansi tidak sehat? Apakah pluralisme berarti bahwa apa pun yang terjadi? Dan apa sebenarnya kriteria untuk menghentikan multiplikasi berpotensi tak berujung ide valid? Menurut Louise Marcil-Lacoste (1992), pluralisme memerlukan ambiguitas tertentu 'antara over-penuh dan kosong': di satu sisi, pluralisme menunjukkan kelimpahan , berbunga dan perluasan nilai dan pilihan, tetapi, di sisi lain, itu juga membangkitkan kekosongan. Untuk mengenali atau mempromosikan pluralitas dalam beberapa konteks adalah untuk mengatakan apa-apa tentang sifat unsur dan isu-isu, hubungan mereka, dan nilai. Berasal dari ini, pluralisme dapat menggabungkan kedua kritik dan penggelapan. Ini melibatkan kritik dari semua monisms dan bertujuan untuk mendekonstruksi klaim dasar mereka. Namun ada juga penggelapan, dalam hal penolakannya untuk mengembangkan posisi normatif substantif mengenai proses sosial, politik dan ekonomi (ibid.).
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
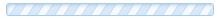
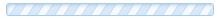
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.
- What does the notice mean ?
- muncrat
- 担当業務についての技能や実務経験を深めていく。 チームや組織内で自らの果たすべき
- MATERI PELAJARANSOAL LampiranRead the fo
- Clicking'Selfie'hasbecomethe fastgrowing
- MATERI PELAJARANSOAL LampiranRead the fo
- relocated
- Saudara
- No honey,I'm still at getting ready for
- yes I know you read my massage thx for r
- Saudara baik
- what do you teenagers think about?
- Vagina Muncrat
- Pernahkah anda membuangnya?
- Optimal Fiscal FederalismAlthough the Ti
- HOT STAMP CACAT TERJADI KARENA BENTURAN
- adik
- The visitors must feed the animals
- 担当業務についての技能や実務経験を深めていく。 チームや組織内で自らの果たすべき
- Have you throw it away?
- Sahabat sejati
- Optimal Fiscal FederalismAlthough the Ti
- saya pikir, saya ingin tidur lagi
- HOT STAMP RUSAK KARENA BENTURAN SAAT PRO

