- Teks
- Sejarah
The conflict with his parents, howe
The conflict with his parents, however, intensifies. He is driven by the need to
express his anguish and torment in his art. “For the unspeakable mystery that brings good
fathers and sons into the world and lets a mother watch them tear at each other’s throats.”
He paints a metaphoric crucifixion scene (he chooses Christian symbolism because
Judaism, he says, offers nothing comparable), his mother with her arms extended above
the window of the family living room, her face split into two segments, his father and he
standing below with an attache case and a palette respectively, demanding the impossible,
that she choose between them.
His parents are deeply shocked by the painting. Even the Rebbe abandons him
this time. “’Asher Lev,’” the Rebbe said softly. ‘You have crossed a boundary. I cannot
help you. You are alone now. I give you my blessings.” At the end of the novel he
leaves Brooklyn for Paris, but he is still “Asher Lev, Hasid. Asher Lev, painter.” He
hears his mythic ancestor: “Come with me, my precious Asher. You and I will walk
together now through the centuries, each of us for our separate deeds that unbalanced the
world.” He will be a great painter, but in doing so he will also continue to hurt the people
he loves. There is no way out of the dilemma.
What is the connection between My Name is Asher Lev and Abdurrahman Wahid?
At the simplest level, his appreciation for the world of Asher Lev reflects his empathic
ability to enter the consciousness of others, remarkable in his case since there is little love
for Jews among most Indonesian Muslims. He read in the novel the Hebrew greeting and
response “Sholom aleichim, aleichim sholom” and saw, he told me, the familiar Arabic
“Salam alaikum, alaikum salam,” used by Indonesian Muslims as a mark of their Islamic
identity, differentiating them from others. To Gus Dur, however, the similarity of the
phrases signified not only the common origins of the two religions but more deeply the
universality of the human religious experience. His love for the novel also helps to
explain his long fascination with Jews and Israel, a country that he has visited several
times as a private citizen and with which he now proposes as president to establish
economic relations.
More deeply, however, the novel is a mirror to Gus Dur for two reasons. First, the
Hasidic yeshiva-centered world described by Potok looks remarkably like the pesantren
or Islamic boarding school-centered world of traditional Indonesian Islam. To be a
student in these schools is to be a member of a moral community possessing shared
values and beliefs that differentiate initiates from outsiders. It is an intense experience
that creates strong lifelong bonds among the students and between them and their
teachers. At the center of both is a respected, even charismatic, leader, the Rebbe or the
Kiai, who is to be obeyed without question. The yeshiva and the pesantren are also
central institutions of the communities they serve, Hasidic Jews and traditional
Indonesian Muslims. The Rebbe and the Kiai are consulted as a matter of course when
serious family or community problems arise, and their advice is rarely rejected.
Second, as strong, even charismatic, leaders the Rebbe and the Kiai have the
principal responsibility for shaping their communities’ futures. In order to respond to the
challenges of their time and place, they must have a broader social and cultural horizon
than their members. They must be bridges to other worlds, non-observant Jewish and
Gentile America in the case of the Hasidic yeshiva, modern Indonesian and global society
and culture in the case of the Muslim pesantren. In this respect the Rebbe in My Name is
Asher Lev affirmed for Gus Dur his own conception of the ideal NU Kiai, a leader who is
firmly rooted in the tradition of classical Sunni Islam and for that very reason is capable
of flexibly interpreting or even reshaping that tradition to meet the challenges of the
modern world. It is the Rebbe, not Asher’s equally pious but intellectually and morally
conventional father, who believes that it is possible to be both an observant Jew and a
great twentieth-century artist. By giving him Jacob Kahn as a teacher (in itself a gesture
natural to the yeshiva tradition), the Rebbe makes Asher’s success outside the Jewish
world possible.
For Gus Dur there is a very personal element in all this. In some respects, he is
both the Rebbe and Asher Lev. His grandfather was the founder of NU, his father a
prominent NU leader, and it was expected that Gus Dur would eventually step into their
shoes. As a boy and young man, however, he was a maverick with a sharp mind,
uncomfortable with conventional Islamic beliefs and practices and eager to expand his
horizons. After his study in Baghdad and Cairo (where he earned no degrees) he spent
time at several European universities before returning home in the mid-1970s. He then
began his career as a Jakarta-based social activist, which included writing over the next
several years a series of remarkable columns in Tempo magazine. Each of these columns
told a story about a wise Rebbe-like Kiai who solves a contemporary social problem that
conventional approaches, based on modern technology or organization alone, could not
overcome.
In these columns it is easy to see the Gus Dur who has always had a chip on his
shoulder, who disdains the modernist Muslims too eager to discard Islamic and
Indonesian history and culture in favor of an unmediated application of the Qur’an to
contemporary life. But his larger purpose was a positive one, and not restricted to the
Muslim community: to demonstrate that traditional roles, values and practices like those
of the Kiai are both necessary to the transition to a modern society and an inescapable
part of the specifically Indonesian modernity that he hoped to build. He was also
implicitly offering himself, though for many years without much hope of success, as a
kind of Kiai-President, a blend of traditional and modern roles.
The concept of a Kiai-President has its strengths and weaknesses. Perhaps its
greatest strength is its familiarity and therefore instant legitimacy to tens of millions of
Indonesians from most regions and ethnic backgrounds. This characteristic will certainly
help the reformers, Gus Dur among them, who are attempting to replace former President
Suharto’s army-backed authoritarian New Order with a more democratic system. Its most
glaring weakness is its lack of rules and procedures through which leaders can be held
accountable to their constituencies. The Kiai achieves his position through a combination
of birth, education, and a gradual acceptance of his knowledge and teaching ability by
other Kiai, potential students and their parents, and the larger traditional Muslim
community. There is no regular procedure by which he is chosen or, perhaps more
importantly, by which he can be removed.
For the most part, therefore, the institutions which hold the president accountable
will have to be borrowed from other traditions, notably that of the West and democratic
East Asia. This process was begun by President B. J. Habibie, the successor to Suharto,
whose government quickly bowed to popular pressure for a free press and democratic
elections. It is continuing under Gus Dur, the first democratically elected president in
Indonesian history. The People’s Consultative Assembly that elected him is now
preparing constitutional amendments and regulations that will constrain future presidents
and insure a greater role for Parliament and an independent judiciary. The new president
has also responded quickly to regional demands to create a de facto federal system, in
which provinces will elect their own legislatures and governors.
Despite its lack of a concept of institutional accountability, traditional Islam may
yet make a significant contribution to Indonesian democratization through Gus Dur the
Kiai-President. Both the Rebbe in My Name is Asher Lev and the many Kiai whose
stories were written down by Gus Dur were distinguished for their combination of deep
roots and an open, flexible, and inclusive approach to outsiders and to the future. In the
end, Asher Lev went too far, crossed a boundary where the Rebbe could not go, leaving
Asher with only his mythic ancestor to accompany him. On his past record, there is a
good chance that Gus Dur will draw the boundaries in a way that will keep the major
players—ethnic and regional as well as religious—inside the nation while moving
steadily toward democratization of the state.
R. William Liddle, Professor of Political Science, The Ohio State University.
express his anguish and torment in his art. “For the unspeakable mystery that brings good
fathers and sons into the world and lets a mother watch them tear at each other’s throats.”
He paints a metaphoric crucifixion scene (he chooses Christian symbolism because
Judaism, he says, offers nothing comparable), his mother with her arms extended above
the window of the family living room, her face split into two segments, his father and he
standing below with an attache case and a palette respectively, demanding the impossible,
that she choose between them.
His parents are deeply shocked by the painting. Even the Rebbe abandons him
this time. “’Asher Lev,’” the Rebbe said softly. ‘You have crossed a boundary. I cannot
help you. You are alone now. I give you my blessings.” At the end of the novel he
leaves Brooklyn for Paris, but he is still “Asher Lev, Hasid. Asher Lev, painter.” He
hears his mythic ancestor: “Come with me, my precious Asher. You and I will walk
together now through the centuries, each of us for our separate deeds that unbalanced the
world.” He will be a great painter, but in doing so he will also continue to hurt the people
he loves. There is no way out of the dilemma.
What is the connection between My Name is Asher Lev and Abdurrahman Wahid?
At the simplest level, his appreciation for the world of Asher Lev reflects his empathic
ability to enter the consciousness of others, remarkable in his case since there is little love
for Jews among most Indonesian Muslims. He read in the novel the Hebrew greeting and
response “Sholom aleichim, aleichim sholom” and saw, he told me, the familiar Arabic
“Salam alaikum, alaikum salam,” used by Indonesian Muslims as a mark of their Islamic
identity, differentiating them from others. To Gus Dur, however, the similarity of the
phrases signified not only the common origins of the two religions but more deeply the
universality of the human religious experience. His love for the novel also helps to
explain his long fascination with Jews and Israel, a country that he has visited several
times as a private citizen and with which he now proposes as president to establish
economic relations.
More deeply, however, the novel is a mirror to Gus Dur for two reasons. First, the
Hasidic yeshiva-centered world described by Potok looks remarkably like the pesantren
or Islamic boarding school-centered world of traditional Indonesian Islam. To be a
student in these schools is to be a member of a moral community possessing shared
values and beliefs that differentiate initiates from outsiders. It is an intense experience
that creates strong lifelong bonds among the students and between them and their
teachers. At the center of both is a respected, even charismatic, leader, the Rebbe or the
Kiai, who is to be obeyed without question. The yeshiva and the pesantren are also
central institutions of the communities they serve, Hasidic Jews and traditional
Indonesian Muslims. The Rebbe and the Kiai are consulted as a matter of course when
serious family or community problems arise, and their advice is rarely rejected.
Second, as strong, even charismatic, leaders the Rebbe and the Kiai have the
principal responsibility for shaping their communities’ futures. In order to respond to the
challenges of their time and place, they must have a broader social and cultural horizon
than their members. They must be bridges to other worlds, non-observant Jewish and
Gentile America in the case of the Hasidic yeshiva, modern Indonesian and global society
and culture in the case of the Muslim pesantren. In this respect the Rebbe in My Name is
Asher Lev affirmed for Gus Dur his own conception of the ideal NU Kiai, a leader who is
firmly rooted in the tradition of classical Sunni Islam and for that very reason is capable
of flexibly interpreting or even reshaping that tradition to meet the challenges of the
modern world. It is the Rebbe, not Asher’s equally pious but intellectually and morally
conventional father, who believes that it is possible to be both an observant Jew and a
great twentieth-century artist. By giving him Jacob Kahn as a teacher (in itself a gesture
natural to the yeshiva tradition), the Rebbe makes Asher’s success outside the Jewish
world possible.
For Gus Dur there is a very personal element in all this. In some respects, he is
both the Rebbe and Asher Lev. His grandfather was the founder of NU, his father a
prominent NU leader, and it was expected that Gus Dur would eventually step into their
shoes. As a boy and young man, however, he was a maverick with a sharp mind,
uncomfortable with conventional Islamic beliefs and practices and eager to expand his
horizons. After his study in Baghdad and Cairo (where he earned no degrees) he spent
time at several European universities before returning home in the mid-1970s. He then
began his career as a Jakarta-based social activist, which included writing over the next
several years a series of remarkable columns in Tempo magazine. Each of these columns
told a story about a wise Rebbe-like Kiai who solves a contemporary social problem that
conventional approaches, based on modern technology or organization alone, could not
overcome.
In these columns it is easy to see the Gus Dur who has always had a chip on his
shoulder, who disdains the modernist Muslims too eager to discard Islamic and
Indonesian history and culture in favor of an unmediated application of the Qur’an to
contemporary life. But his larger purpose was a positive one, and not restricted to the
Muslim community: to demonstrate that traditional roles, values and practices like those
of the Kiai are both necessary to the transition to a modern society and an inescapable
part of the specifically Indonesian modernity that he hoped to build. He was also
implicitly offering himself, though for many years without much hope of success, as a
kind of Kiai-President, a blend of traditional and modern roles.
The concept of a Kiai-President has its strengths and weaknesses. Perhaps its
greatest strength is its familiarity and therefore instant legitimacy to tens of millions of
Indonesians from most regions and ethnic backgrounds. This characteristic will certainly
help the reformers, Gus Dur among them, who are attempting to replace former President
Suharto’s army-backed authoritarian New Order with a more democratic system. Its most
glaring weakness is its lack of rules and procedures through which leaders can be held
accountable to their constituencies. The Kiai achieves his position through a combination
of birth, education, and a gradual acceptance of his knowledge and teaching ability by
other Kiai, potential students and their parents, and the larger traditional Muslim
community. There is no regular procedure by which he is chosen or, perhaps more
importantly, by which he can be removed.
For the most part, therefore, the institutions which hold the president accountable
will have to be borrowed from other traditions, notably that of the West and democratic
East Asia. This process was begun by President B. J. Habibie, the successor to Suharto,
whose government quickly bowed to popular pressure for a free press and democratic
elections. It is continuing under Gus Dur, the first democratically elected president in
Indonesian history. The People’s Consultative Assembly that elected him is now
preparing constitutional amendments and regulations that will constrain future presidents
and insure a greater role for Parliament and an independent judiciary. The new president
has also responded quickly to regional demands to create a de facto federal system, in
which provinces will elect their own legislatures and governors.
Despite its lack of a concept of institutional accountability, traditional Islam may
yet make a significant contribution to Indonesian democratization through Gus Dur the
Kiai-President. Both the Rebbe in My Name is Asher Lev and the many Kiai whose
stories were written down by Gus Dur were distinguished for their combination of deep
roots and an open, flexible, and inclusive approach to outsiders and to the future. In the
end, Asher Lev went too far, crossed a boundary where the Rebbe could not go, leaving
Asher with only his mythic ancestor to accompany him. On his past record, there is a
good chance that Gus Dur will draw the boundaries in a way that will keep the major
players—ethnic and regional as well as religious—inside the nation while moving
steadily toward democratization of the state.
R. William Liddle, Professor of Political Science, The Ohio State University.
0/5000
Konflik dengan orangtuanya, namun, meningkat. Dia didorong oleh kebutuhan untukCheck penderitaan dan siksaan dalam seni nya. "Untuk misteri tak terkatakan yang membawa baikayah dan anak ke dunia dan memungkinkan seorang ibu menonton mereka merobek di tenggorokan satu sama lain. "Ia cat adegan metaforik penyaliban (dipilihnya simbolisme Kristian karenaYudaisme, katanya, menawarkan tidak sebanding), diperpanjang ibunya dengan tangan di atasjendela ruang tamu Keluarga, wajahnya dibagi menjadi dua segmen, ayahnya, dan iaberdiri di bawah dengan kasus Atase dan palet masing-masing, menuntut yang mustahil,Dia memilih antara mereka.Orang tuanya sangat terkejut oleh lukisan. Bahkan Rebbe meninggalkan Dia.Saat ini. "' Asher Lev,'" kata Rebbe lembut. ' Anda telah melintasi batas. Saya tidak bisamembantu Anda. Anda tidak sendirian. Saya memberi Anda berkat-Ku." Pada akhir novel diadaun Brooklyn untuk Paris, tapi dia masih "Asyer Lev, Hasid. Lev Asyer, pelukis." Diamendengar leluhurnya mitis: "Ayo dengan saya, saya berharga Asyer. Anda dan saya akan berjalanbersama-sama sekarang melalui berabad-abad, masing-masing dari kita untuk kita terpisah perbuatan yang tidak seimbangdunia." Ia akan menjadi seorang pelukis yang besar, tetapi dengan begitu ia juga akan terus menyakiti orang-orangDia mengasihi. Ada ada jalan keluar dari dilema.Apa hubungan antara namaku adalah Lev Asyer dan Abdurrahman Wahid?Pada tingkatan yang sederhana, apresiasi atas dunia Asyer Lev mencerminkan nya empatikkemampuan untuk memasuki kesadaran orang lain, luar biasa dalam kasus ini karena ada sedikit cintaorang Yahudi antara kebanyakan Muslim Indonesia. Dia membaca dalam novel salam Ibrani danrespon "Memiliki galeri mengenai: aleichim, aleichim memiliki galeri mengenai:" dan saw, dia mengatakan kepada saya, bahasa Arab akrab"Salam alaikum, alaikum salam," digunakan oleh umat Islam Indonesia sebagai tanda mereka Islamidentitas, membedakan mereka dari orang lain. Untuk Gus Dur, namun, kesamaanfrasa menandakan tidak hanya asal-usul umum dari dua agama tetapi lebih mendalamuniversalitas pengalaman agama manusia. Kasih-Nya bagi novel juga membantu untukmenjelaskan kekagumannya panjang dengan orang Yahudi dan Israel, bahwa ia telah mengunjungi beberapa negarakali sebagai warga negara dan dengan yang ia sekarang mengusulkan sebagai Presiden untuk mendirikanhubungan ekonomi.Lebih dalam, namun, novel adalah cermin untuk Gus Dur untuk dua alasan. Pertama,Hasidic yeshiva-pusat dunia digambarkan oleh Potok terlihat persis seperti pesantrenatau dunia yang berpusat pada sekolah asrama Islam tradisional Islam Indonesia. Menjadisiswa di sekolah ini adalah untuk menjadi anggota sebuah komunitas moral memiliki bersamanilai-nilai dan keyakinan yang membedakan memulai dari luar. Itu adalah pengalaman yang intensyang menciptakan ikatan seumur hidup yang kuat antara siswa dan di antara mereka dan merekaguru. Di tengah-tengah kedua adalah seorang pemimpin yang dihormati, bahkan karismatik, Rebbe atauKiai, yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Yeshiva dan pesantrenlembaga-lembaga pusat komunitas mereka melayani, Hasidic Yahudi dan tradisionalMuslim Indonesia. Rebbe dan Kiai yang berkonsultasi sebagai masalah tentu saja Kapantimbul masalah serius keluarga atau komunitas, dan nasihat mereka jarang ditolak.Kedua, sebagai pemimpin yang kuat, bahkan karismatik, Rebbe dan Kiai memilikitanggung jawab utama untuk membentuk masa depan komunitas mereka. Menanggapitantangan mereka waktu dan tempat, mereka harus memiliki luas cakrawala sosial dan budayadaripada anggota-anggota mereka. Mereka harus menjadi jembatan ke dunia lain, sekuler Yahudi danBangsa Amerika dalam kasus yeshiva Hasidic, masyarakat modern Indonesia dan globaldan budaya dalam kasus Muslim pesantren. Dalam hal ini adalah Rebbe dalam nama-KuLev Asyer menegaskan untuk Gus Dur sendiri konsepsi Kiai NU ideal, seorang pemimpin yang telahberakar dalam tradisi klasik Islam Sunni dan untuk alasan mampufleksibel menafsirkan atau bahkan penyusunan kembali tradisi itu untuk memenuhi tantangandunia modern. Itu adalah Rebbe, tidak Asyer sama saleh tetapi intelektual dan moralBapa konvensional, yang percaya bahwa mungkin untuk menjadi baik Yahudi jeli danseniman besar abad. Dengan memberinya Jacob Kahn sebagai guru (sendiri sikapalam tradisi yeshiva), Rebbe membuat Asyer 's kesuksesan di luar Yahudimungkin dunia.Untuk Gus Dur ada unsur yang sangat pribadi dalam semua ini. Dalam beberapa hal, ia adalahkedua Rebbe dan Lev Asyer. Kakeknya adalah pendiri NU, ayahnyamenonjol NU pemimpin, dan diharapkan bahwa Gus Dur akan akhirnya masuk ke merekaSepatu. Sebagai seorang anak laki-laki dan pemuda, namun, ia adalah maverick dengan pikiran yang tajam,nyaman dengan keyakinan Islam konvensional dan praktek-praktek dan bersemangat untuk memperluas nyacakrawala. Setelah kuliah di Baghdad dan Kairo (di mana ia menerima gelar tidak) ia menghabiskanwaktu di beberapa perguruan tinggi Eropa sebelum pulang pada pertengahan 1970-an. Ia kemudianmemulai karirnya sebagai berbasis di Jakarta aktivis sosial, yang termasuk tulisan berikutnyabeberapa tahun serangkaian kolom yang luar biasa dalam majalah Tempo. Masing-masing kolom inimenceritakan sebuah kisah tentang seorang Kyai Rebbe-seperti yang bijaksana yang memecahkan masalah sosial kontemporer yangpendekatan konvensional, didasarkan pada teknologi modern atau organisasi sendirian, tidak bisamengatasi.Dalam kolom ini sangat mudah untuk melihat Gus Dur yang selalu memiliki chip nyabahu, yang membenci modernis Muslim terlalu bersemangat untuk membuang Islam danSejarah Indonesia dan budaya mendukung aplikasi unmediated Al Qur'an untukkehidupan kontemporer. Tetapi tujuannya yang lebih besar yang positif, dan tidak terbatasKomunitas Muslim: untuk menunjukkan bahwa peran tradisional, nilai-nilai dan praktik seperti merekadari Kiai keduanya diperlukan untuk transisi ke masyarakat modern dan tak terhindarkanBagian dari modernitas khusus Indonesia bahwa dia berharap untuk membangun. Dia adalah jugasecara implisit mempersembahkan dirinya, meskipun selama bertahun-tahun tanpa banyak harapan sukses, sebagaijenis Kiai-Presiden, perpaduan tradisional dan modern peran.Konsep Kiai-Presiden memiliki kekuatan dan kelemahan. Mungkin yangkekuatan terbesarnya adalah keakraban dan karenanya instan legitimasi untuk puluhan jutaIndonesia dari sebagian wilayah dan latar belakang etnis. Karakteristik ini pasti akanmembantu para reformer, Gus Dur di antara mereka, yang sedang berusaha untuk menggantikan mantan PresidenSuharto di tentara didukung otoriter Orde Baru dengan sistem yang lebih demokratis. Kebanyakan paramencolok kelemahan adalah karena kurangnya peraturan dan prosedur di mana pemimpin dapat diselenggarakanbertanggung jawab kepada konstituen mereka. Kiai mencapai posisinya melalui kombinasikelahiran, pendidikan, dan penerimaan yang bertahap pengetahuan dan kemampuan dengan pengajaranKiai lainnya, potensi siswa dan orangtua mereka, dan orang Muslim tradisional yang lebih besarkomunitas. Ada tidak ada prosedur biasa yang Dialah yang dipilih atau, mungkin lebihpenting, yang ia dapat dihilangkan.Untuk sebagian besar, oleh karena itu, lembaga-lembaga yang pertanggungjawaban Presidenharus dipinjam dari tradisi lainnya, terutama yang dari Barat dan demokrasiAsia Timur. Proses ini dimulai oleh Presiden B. J. Habibie, penerus Soeharto,pemerintah yang cepat membungkuk kepada tekanan populer untuk pers bebas dan demokratispemilihan umum. It's terus di bawah Gus Dur, Presiden pertama yang dipilih secara demokratis diSejarah Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih dia kinimempersiapkan Amandemen Konstitusi dan peraturan yang akan membatasi Presiden masa depandan memastikan peran yang lebih besar untuk Parlemen dan independensi sistem peradilan. Presiden barutelah juga menanggapi dengan cepat ke daerah tuntutan untuk menciptakan sistem federal secara de facto, diProvinsi yang akan memilih Gubernur dan legislatif sendiri.Meskipun kurangnya konsep akuntabilitas kelembagaan, tradisional Islam mungkinNamun membuat kontribusi yang signifikan terhadap demokratisasi Indonesia melalui Gus DurKiai-Presiden. Kedua Rebbe dalam nama-Ku adalah Lev Asyer dan Kiai banyak yangcerita ditulis oleh Gus Dur dibedakan untuk kombinasi mereka yang mendalamakar dan pendekatan terbuka, fleksibel dan inklusif luar dan masa depan. DalamAkhirnya, Lev Asyer pergi terlalu jauh, melintasi batas mana Rebbe tidak pergi, meninggalkanAsyer dengan hanya leluhurnya mitis untuk menemaninya. Pada masa lalunya catatan, adakesempatan baik bahwa Gus Dur akan menarik batas-batas dengan cara yang akan tetap utamapemain — etnis dan daerah serta agama — di dalam bangsa sambil bergerakterus menuju demokratisasi negara.R. misal: Liddle William, profesor ilmu politik, Ohio State University
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
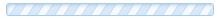
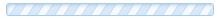
Konflik dengan orang tuanya, bagaimanapun, mengintensifkan. Dia didorong oleh kebutuhan untuk
mengekspresikan kesedihan dan siksaan-Nya dalam seni. "Untuk misteri tak terkatakan yang membawa baik
ayah dan anak ke dunia dan memungkinkan seorang ibu melihat mereka robek di leher masing-masing. "
Dia melukis adegan penyaliban metaforis (ia memilih simbolisme Kristen karena
Yudaisme, katanya, menawarkan apa-apa dibandingkan), nya ibu dengan tangan diperpanjang di atas
jendela ruang tamu keluarga, wajahnya dibagi menjadi dua segmen, ayahnya dan ia
berdiri di bawah ini dengan kasus atase dan palet masing-masing, menuntut mustahil,
bahwa dia memilih di antara mereka. Orang tuanya adalah sangat terkejut dengan lukisan. Bahkan Rebbe meninggalkan dia saat ini. "'Asher Lev," kata Rebbe lembut. "Anda telah menyeberangi batas. Aku tidak bisa membantu Anda. Anda sendirian sekarang. Saya memberikan berkat saya. "Pada akhir novel ia meninggalkan Brooklyn untuk Paris, namun ia masih "Asher Lev, Hasid. . Asher Lev, pelukis "Dia mendengar nenek mitosnya: "Mari ikut saya, Asher berharga. Kau dan aku akan berjalan bersama-sama sekarang selama berabad-abad, kita masing-masing untuk perbuatan yang terpisah kita yang tidak seimbang dalam dunia. "Dia akan menjadi seorang pelukis besar, tetapi dengan begitu ia juga akan terus menyakiti orang yang dicintainya. Tidak ada jalan keluar dari dilema. Apa hubungan antara My Name is Asher Lev dan Abdurrahman Wahid? Pada tingkat yang paling sederhana, apresiasi atas dunia Asher Lev mencerminkan empati nya kemampuan untuk memasuki kesadaran orang lain, luar biasa dalam nya terjadi sejak ada sedikit cinta untuk orang-orang Yahudi di antara sebagian besar umat Islam Indonesia. Dia membaca dalam novel ucapan Ibrani dan respon "Sholom aleichim, aleichim Sholom" dan melihat, dia mengatakan kepada saya, akrab Arab "Salam alaikum, alaikum salam," digunakan oleh umat Islam Indonesia sebagai tanda Islam mereka identitas, membedakan mereka dari lain. Untuk Gus Dur, namun kesamaan frasa menandakan tidak hanya asal-usul umum dari kedua agama tetapi lebih dalam universalitas pengalaman religius manusia. Kasih-Nya bagi novel juga membantu untuk menjelaskan daya tarik panjang dengan Yahudi dan Israel, sebuah negara bahwa ia telah mengunjungi beberapa kali sebagai warga sipil dan yang ia sekarang mengusulkan sebagai presiden untuk membangun hubungan ekonomi. Lebih dalam, bagaimanapun, novel ini cermin untuk Gus Dur karena dua alasan. Pertama, Hasid yeshiva berpusat dunia dijelaskan oleh Potok terlihat sangat seperti pesantren atau Islam dunia pesantren yang berpusat Islam tradisional Indonesia. Untuk menjadi siswa di sekolah ini adalah untuk menjadi anggota komunitas moral yang memiliki bersama nilai-nilai dan keyakinan yang membedakan inisiat dari luar. Ini adalah pengalaman yang intens yang menciptakan ikatan seumur hidup yang kuat di kalangan mahasiswa dan di antara mereka dan mereka guru. Di tengah-tengah kedua adalah dihormati, bahkan karismatik, pemimpin, Rebbe atau Kiai, yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Yeshiva dan pesantren juga lembaga sentral dari masyarakat yang mereka layani, Hasid Yahudi dan tradisional Muslim Indonesia. Rebbe dan Kiai dikonsultasikan sebagai hal yang biasa ketika keluarga atau masyarakat masalah serius muncul, dan saran mereka jarang ditolak. Kedua, kuat, bahkan karismatik, pemimpin Rebbe dan Kiai memiliki tanggung jawab utama untuk membentuk komunitas mereka ' berjangka. Untuk menanggapi tantangan waktu dan tempat, mereka harus memiliki cakrawala yang lebih luas sosial dan budaya dari anggotanya. Mereka harus jembatan ke dunia lain, non-jeli Yahudi dan non-Yahudi Amerika dalam kasus yeshiva Hasid, masyarakat Indonesia dan global yang modern dan budaya dalam kasus pesantren Islam. Dalam hal ini Rebbe di Nama saya Asher Lev menegaskan untuk Gus Dur konsepsi sendiri yang ideal NU Kiai, seorang pemimpin yang berakar kuat dalam tradisi klasik Islam Sunni dan untuk alasan itu mampu dari fleksibel menafsirkan atau bahkan membentuk kembali Tradisi itu untuk memenuhi tantangan dunia modern. Ini adalah Rebbe, tidak Asher sama saleh tapi secara intelektual dan moral konvensional ayah, yang percaya bahwa adalah mungkin untuk menjadi seorang Yahudi yang taat dan seniman abad kedua puluh besar. Dengan memberinya Jacob Kahn sebagai guru (sendiri merupakan gerakan alami dengan tradisi yeshiva), Rebbe membuat kesuksesan Asher di luar Yahudi dunia mungkin. Untuk Gus Dur ada unsur yang sangat pribadi dalam semua ini. Dalam beberapa hal, dia baik Rebbe dan Asher Lev. Kakeknya adalah pendiri NU, ayahnya seorang pemimpin terkemuka NU, dan diharapkan bahwa Gus Dur akhirnya akan masuk ke mereka sepatu. Sebagai anak laki-laki dan laki-laki muda, bagaimanapun, dia adalah seorang maverick dengan pikiran yang tajam, tidak nyaman dengan keyakinan Islam konvensional dan praktik dan bersemangat untuk memperluas cakrawala. Setelah studinya di Baghdad dan Kairo (di mana ia meraih gelar ada) ia menghabiskan waktu di beberapa universitas di Eropa sebelum pulang pada pertengahan 1970-an. Dia kemudian memulai karirnya sebagai aktivis sosial yang berbasis di Jakarta, yang termasuk menulis selama berikutnya beberapa tahun serangkaian kolom yang luar biasa di majalah Tempo. Masing-masing kolom ini bercerita tentang seorang yang bijaksana Rebbe seperti Kiai yang memecahkan masalah sosial kontemporer yang pendekatan konvensional, didasarkan pada teknologi modern atau organisasi saja, tidak bisa diatasi. Dalam kolom ini mudah untuk melihat Gus Dur yang selalu memiliki chip di nya bahu, yang meremehkan kaum Muslim modernis terlalu bersemangat untuk membuang Islam dan sejarah dan budaya Indonesia dalam mendukung aplikasi unmediated dari Al-Qur'an untuk kehidupan kontemporer. Tapi tujuannya lebih besar adalah positif, dan tidak terbatas pada komunitas Muslim: untuk menunjukkan bahwa peran tradisional, nilai-nilai dan praktik-praktik seperti yang dari Kiai keduanya diperlukan untuk transisi ke masyarakat modern dan tak terhindarkan bagian dari modernitas khusus Indonesia bahwa ia berharap untuk membangun. Dia juga secara implisit menawarkan dirinya, meskipun selama bertahun-tahun tanpa banyak harapan keberhasilan, sebagai semacam Kiai Presiden, perpaduan peran tradisional dan modern. Konsep Kiai Presiden memiliki kekuatan dan kelemahan. Mungkin yang kekuatan terbesar adalah keakraban dan legitimasi karena itu cepat ke puluhan juta orang Indonesia dari sebagian besar daerah dan latar belakang etnis. Karakteristik ini tentu akan membantu para reformis, Gus Dur di antara mereka, yang berusaha untuk menggantikan mantan Presiden Orde Soeharto yang didukung militer otoriter baru dengan sistem yang lebih demokratis. Paling yang kelemahan mencolok adalah kurangnya peraturan dan prosedur di mana pemimpin dapat bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Kiai mencapai posisinya melalui kombinasi lahir, pendidikan, dan penerimaan bertahap pengetahuan dan kemampuan mengajar dengan lainnya Kiai, potensi siswa dan orang tua mereka, dan Muslim tradisional yang lebih besar masyarakat. Tidak ada prosedur rutin yang ia dipilih atau, mungkin lebih penting, di mana ia dapat dihapus. Untuk sebagian besar, oleh karena itu, lembaga-lembaga yang memegang presiden bertanggung jawab akan harus dipinjam dari tradisi-tradisi lain, khususnya yang dari Barat dan demokrasi Asia Timur. Proses ini dimulai oleh Presiden BJ Habibie, pengganti Suharto, yang pemerintahnya cepat tunduk pada tekanan populer untuk pers yang bebas dan demokratis pemilu. Hal ini terus di bawah Gus Dur, presiden terpilih secara demokratis pertama dalam sejarah Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terpilih dia kini mempersiapkan amandemen konstitusi dan peraturan yang akan membatasi presiden masa depan dan memastikan peran yang lebih besar untuk Parlemen dan peradilan yang independen. Presiden baru juga telah merespon dengan cepat tuntutan daerah untuk membuat facto sistem federal yang de, di mana provinsi akan memilih legislatif dan gubernur sendiri. Meskipun kurangnya konsep akuntabilitas kelembagaan, Islam tradisional mungkin belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap demokratisasi Indonesia melalui Gus Dur yang Kiai Presiden. Baik Rebbe dalam My Name is Asher Lev dan banyak Kiai yang cerita yang ditulis oleh Gus Dur dibedakan untuk kombinasi mereka dalam akar dan pendekatan terbuka, fleksibel, dan inklusif bagi orang luar dan ke masa depan. Pada akhirnya, Asher Lev pergi terlalu jauh, melintasi batas di mana Rebbe tidak bisa pergi, meninggalkan Asher dengan hanya nenek moyang mitis untuk menemaninya. Pada catatan masa lalunya, ada kesempatan baik bahwa Gus Dur akan menarik batas-batas dengan cara yang akan menjaga utama pemain-etnis dan regional serta agama-dalam bangsa saat bergerak terus ke arah demokratisasi negara. R. William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik, The Ohio State University.
mengekspresikan kesedihan dan siksaan-Nya dalam seni. "Untuk misteri tak terkatakan yang membawa baik
ayah dan anak ke dunia dan memungkinkan seorang ibu melihat mereka robek di leher masing-masing. "
Dia melukis adegan penyaliban metaforis (ia memilih simbolisme Kristen karena
Yudaisme, katanya, menawarkan apa-apa dibandingkan), nya ibu dengan tangan diperpanjang di atas
jendela ruang tamu keluarga, wajahnya dibagi menjadi dua segmen, ayahnya dan ia
berdiri di bawah ini dengan kasus atase dan palet masing-masing, menuntut mustahil,
bahwa dia memilih di antara mereka. Orang tuanya adalah sangat terkejut dengan lukisan. Bahkan Rebbe meninggalkan dia saat ini. "'Asher Lev," kata Rebbe lembut. "Anda telah menyeberangi batas. Aku tidak bisa membantu Anda. Anda sendirian sekarang. Saya memberikan berkat saya. "Pada akhir novel ia meninggalkan Brooklyn untuk Paris, namun ia masih "Asher Lev, Hasid. . Asher Lev, pelukis "Dia mendengar nenek mitosnya: "Mari ikut saya, Asher berharga. Kau dan aku akan berjalan bersama-sama sekarang selama berabad-abad, kita masing-masing untuk perbuatan yang terpisah kita yang tidak seimbang dalam dunia. "Dia akan menjadi seorang pelukis besar, tetapi dengan begitu ia juga akan terus menyakiti orang yang dicintainya. Tidak ada jalan keluar dari dilema. Apa hubungan antara My Name is Asher Lev dan Abdurrahman Wahid? Pada tingkat yang paling sederhana, apresiasi atas dunia Asher Lev mencerminkan empati nya kemampuan untuk memasuki kesadaran orang lain, luar biasa dalam nya terjadi sejak ada sedikit cinta untuk orang-orang Yahudi di antara sebagian besar umat Islam Indonesia. Dia membaca dalam novel ucapan Ibrani dan respon "Sholom aleichim, aleichim Sholom" dan melihat, dia mengatakan kepada saya, akrab Arab "Salam alaikum, alaikum salam," digunakan oleh umat Islam Indonesia sebagai tanda Islam mereka identitas, membedakan mereka dari lain. Untuk Gus Dur, namun kesamaan frasa menandakan tidak hanya asal-usul umum dari kedua agama tetapi lebih dalam universalitas pengalaman religius manusia. Kasih-Nya bagi novel juga membantu untuk menjelaskan daya tarik panjang dengan Yahudi dan Israel, sebuah negara bahwa ia telah mengunjungi beberapa kali sebagai warga sipil dan yang ia sekarang mengusulkan sebagai presiden untuk membangun hubungan ekonomi. Lebih dalam, bagaimanapun, novel ini cermin untuk Gus Dur karena dua alasan. Pertama, Hasid yeshiva berpusat dunia dijelaskan oleh Potok terlihat sangat seperti pesantren atau Islam dunia pesantren yang berpusat Islam tradisional Indonesia. Untuk menjadi siswa di sekolah ini adalah untuk menjadi anggota komunitas moral yang memiliki bersama nilai-nilai dan keyakinan yang membedakan inisiat dari luar. Ini adalah pengalaman yang intens yang menciptakan ikatan seumur hidup yang kuat di kalangan mahasiswa dan di antara mereka dan mereka guru. Di tengah-tengah kedua adalah dihormati, bahkan karismatik, pemimpin, Rebbe atau Kiai, yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Yeshiva dan pesantren juga lembaga sentral dari masyarakat yang mereka layani, Hasid Yahudi dan tradisional Muslim Indonesia. Rebbe dan Kiai dikonsultasikan sebagai hal yang biasa ketika keluarga atau masyarakat masalah serius muncul, dan saran mereka jarang ditolak. Kedua, kuat, bahkan karismatik, pemimpin Rebbe dan Kiai memiliki tanggung jawab utama untuk membentuk komunitas mereka ' berjangka. Untuk menanggapi tantangan waktu dan tempat, mereka harus memiliki cakrawala yang lebih luas sosial dan budaya dari anggotanya. Mereka harus jembatan ke dunia lain, non-jeli Yahudi dan non-Yahudi Amerika dalam kasus yeshiva Hasid, masyarakat Indonesia dan global yang modern dan budaya dalam kasus pesantren Islam. Dalam hal ini Rebbe di Nama saya Asher Lev menegaskan untuk Gus Dur konsepsi sendiri yang ideal NU Kiai, seorang pemimpin yang berakar kuat dalam tradisi klasik Islam Sunni dan untuk alasan itu mampu dari fleksibel menafsirkan atau bahkan membentuk kembali Tradisi itu untuk memenuhi tantangan dunia modern. Ini adalah Rebbe, tidak Asher sama saleh tapi secara intelektual dan moral konvensional ayah, yang percaya bahwa adalah mungkin untuk menjadi seorang Yahudi yang taat dan seniman abad kedua puluh besar. Dengan memberinya Jacob Kahn sebagai guru (sendiri merupakan gerakan alami dengan tradisi yeshiva), Rebbe membuat kesuksesan Asher di luar Yahudi dunia mungkin. Untuk Gus Dur ada unsur yang sangat pribadi dalam semua ini. Dalam beberapa hal, dia baik Rebbe dan Asher Lev. Kakeknya adalah pendiri NU, ayahnya seorang pemimpin terkemuka NU, dan diharapkan bahwa Gus Dur akhirnya akan masuk ke mereka sepatu. Sebagai anak laki-laki dan laki-laki muda, bagaimanapun, dia adalah seorang maverick dengan pikiran yang tajam, tidak nyaman dengan keyakinan Islam konvensional dan praktik dan bersemangat untuk memperluas cakrawala. Setelah studinya di Baghdad dan Kairo (di mana ia meraih gelar ada) ia menghabiskan waktu di beberapa universitas di Eropa sebelum pulang pada pertengahan 1970-an. Dia kemudian memulai karirnya sebagai aktivis sosial yang berbasis di Jakarta, yang termasuk menulis selama berikutnya beberapa tahun serangkaian kolom yang luar biasa di majalah Tempo. Masing-masing kolom ini bercerita tentang seorang yang bijaksana Rebbe seperti Kiai yang memecahkan masalah sosial kontemporer yang pendekatan konvensional, didasarkan pada teknologi modern atau organisasi saja, tidak bisa diatasi. Dalam kolom ini mudah untuk melihat Gus Dur yang selalu memiliki chip di nya bahu, yang meremehkan kaum Muslim modernis terlalu bersemangat untuk membuang Islam dan sejarah dan budaya Indonesia dalam mendukung aplikasi unmediated dari Al-Qur'an untuk kehidupan kontemporer. Tapi tujuannya lebih besar adalah positif, dan tidak terbatas pada komunitas Muslim: untuk menunjukkan bahwa peran tradisional, nilai-nilai dan praktik-praktik seperti yang dari Kiai keduanya diperlukan untuk transisi ke masyarakat modern dan tak terhindarkan bagian dari modernitas khusus Indonesia bahwa ia berharap untuk membangun. Dia juga secara implisit menawarkan dirinya, meskipun selama bertahun-tahun tanpa banyak harapan keberhasilan, sebagai semacam Kiai Presiden, perpaduan peran tradisional dan modern. Konsep Kiai Presiden memiliki kekuatan dan kelemahan. Mungkin yang kekuatan terbesar adalah keakraban dan legitimasi karena itu cepat ke puluhan juta orang Indonesia dari sebagian besar daerah dan latar belakang etnis. Karakteristik ini tentu akan membantu para reformis, Gus Dur di antara mereka, yang berusaha untuk menggantikan mantan Presiden Orde Soeharto yang didukung militer otoriter baru dengan sistem yang lebih demokratis. Paling yang kelemahan mencolok adalah kurangnya peraturan dan prosedur di mana pemimpin dapat bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Kiai mencapai posisinya melalui kombinasi lahir, pendidikan, dan penerimaan bertahap pengetahuan dan kemampuan mengajar dengan lainnya Kiai, potensi siswa dan orang tua mereka, dan Muslim tradisional yang lebih besar masyarakat. Tidak ada prosedur rutin yang ia dipilih atau, mungkin lebih penting, di mana ia dapat dihapus. Untuk sebagian besar, oleh karena itu, lembaga-lembaga yang memegang presiden bertanggung jawab akan harus dipinjam dari tradisi-tradisi lain, khususnya yang dari Barat dan demokrasi Asia Timur. Proses ini dimulai oleh Presiden BJ Habibie, pengganti Suharto, yang pemerintahnya cepat tunduk pada tekanan populer untuk pers yang bebas dan demokratis pemilu. Hal ini terus di bawah Gus Dur, presiden terpilih secara demokratis pertama dalam sejarah Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terpilih dia kini mempersiapkan amandemen konstitusi dan peraturan yang akan membatasi presiden masa depan dan memastikan peran yang lebih besar untuk Parlemen dan peradilan yang independen. Presiden baru juga telah merespon dengan cepat tuntutan daerah untuk membuat facto sistem federal yang de, di mana provinsi akan memilih legislatif dan gubernur sendiri. Meskipun kurangnya konsep akuntabilitas kelembagaan, Islam tradisional mungkin belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap demokratisasi Indonesia melalui Gus Dur yang Kiai Presiden. Baik Rebbe dalam My Name is Asher Lev dan banyak Kiai yang cerita yang ditulis oleh Gus Dur dibedakan untuk kombinasi mereka dalam akar dan pendekatan terbuka, fleksibel, dan inklusif bagi orang luar dan ke masa depan. Pada akhirnya, Asher Lev pergi terlalu jauh, melintasi batas di mana Rebbe tidak bisa pergi, meninggalkan Asher dengan hanya nenek moyang mitis untuk menemaninya. Pada catatan masa lalunya, ada kesempatan baik bahwa Gus Dur akan menarik batas-batas dengan cara yang akan menjaga utama pemain-etnis dan regional serta agama-dalam bangsa saat bergerak terus ke arah demokratisasi negara. R. William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik, The Ohio State University.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
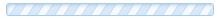
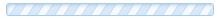
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.
- Waktunya bermusik
- Aku hanya ingin kamu jujur,,jadi aku tid
- Sepuluh
- mangga
- Aku akan selalu samagat dalam hidup
- Begitu besarnya rasa sayangku pada muDar
- pak kalau misalkan seperti ini , begini,
- Who will tell me how
- just for you
- apel
- just for you
- menjijikan
- Who will tell me how
- Tujuh
- just for you
- salam kenal, dan ini nomor saya
- Begitu besarnya rasa sayangku pada muDar
- Delapan
- Aku akan selalu samangat dalam hidup
- Can you tell me how to get to bank from
- Kamu mau ngajak aku keluar?
- Can you tell me how to get to bank from
- Take it easy. I am still waiting, until
- ana adalah anak yang rajin. dia selalu m

